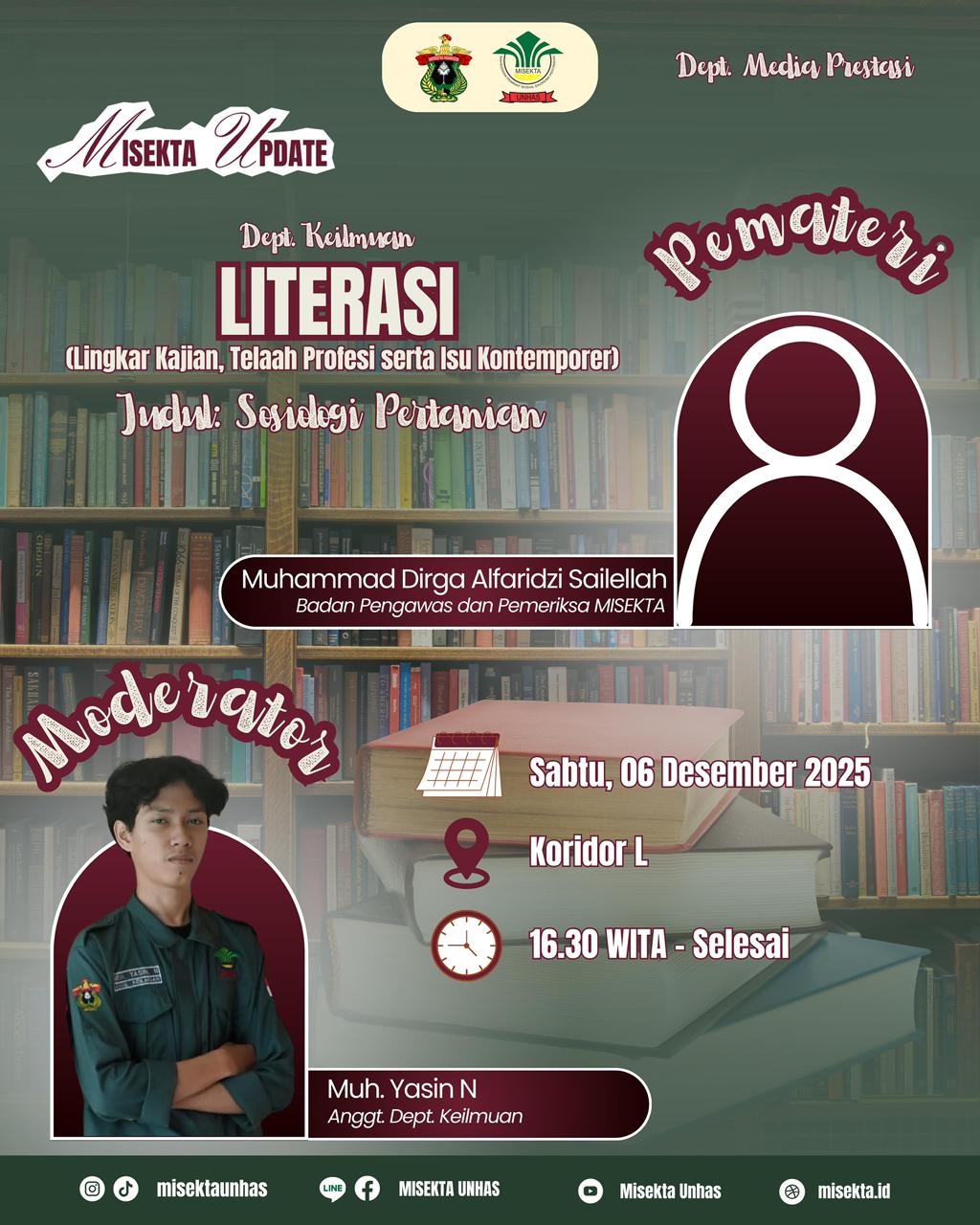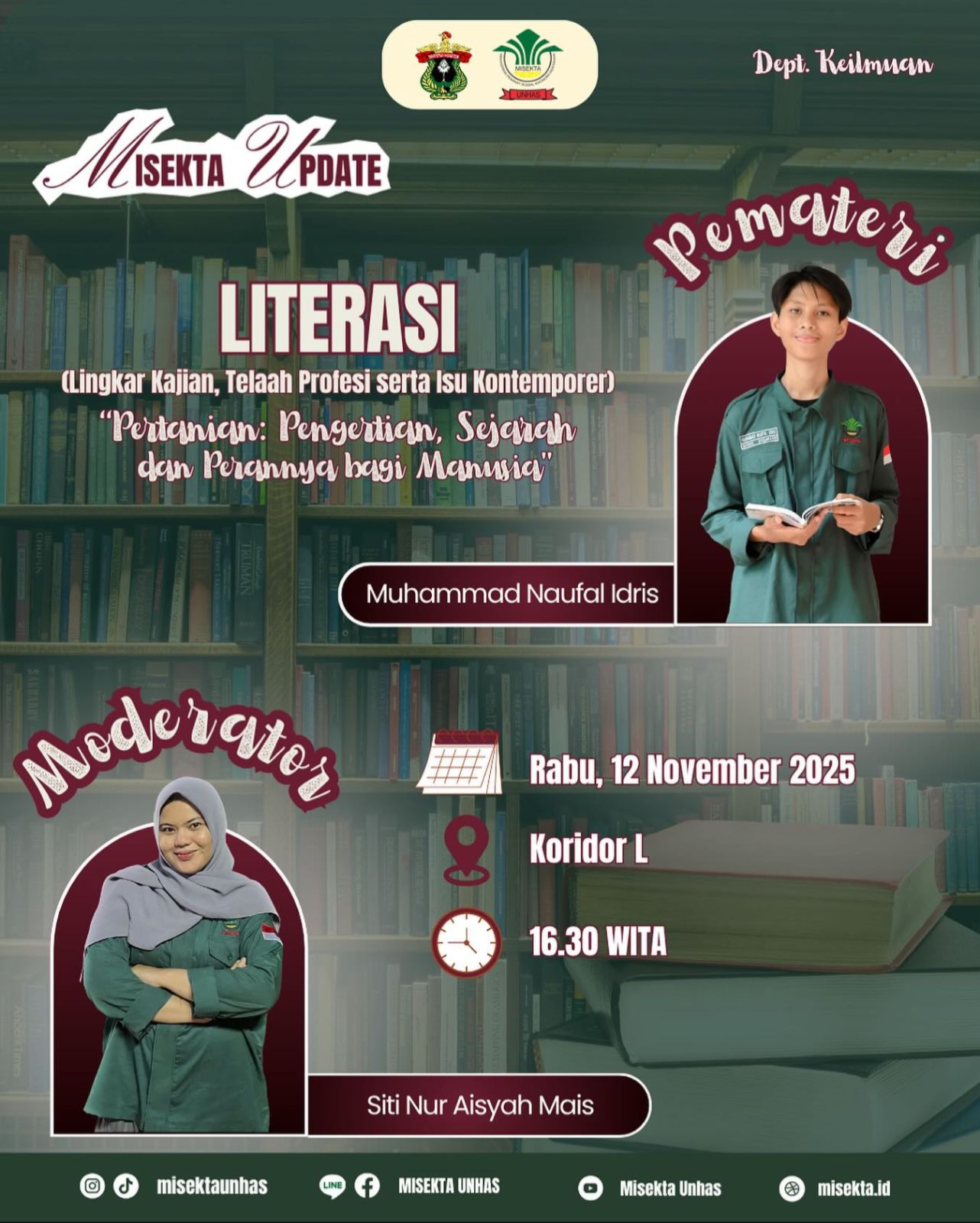Bedah Artikel: Hidup Mati Petani Kita: Dihimpit Neoliberalisme dan Kerakusan Negara
Saturday, 08 February 2025 , Admin

Artikel Hidup Mati Petani Kita: Dihimpit Neoliberalisme dan Kerakusan Negara membahas berbagai permasalahan yang dihadapi petani di Indonesia akibat kebijakan negara dan ekspansi kapitalisme. Meskipun Hari Tani Nasional diperingati setiap 24 September untuk mengenang perjuangan petani, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa mereka masih mengalami kesulitan besar, termasuk perampasan lahan, ketimpangan akses terhadap sumber daya, hingga dampak krisis iklim yang semakin memperburuk kondisi pertanian.
Salah satu persoalan utama dalam konflik agraria adalah bagaimana kapitalisme dan negara berkolaborasi dalam memperluas kepentingan ekonomi mereka dengan mengorbankan kehidupan petani. Banyak kebijakan yang lebih berpihak kepada korporasi besar, baik dalam sektor perkebunan, pertambangan, maupun infrastruktur. Berbagai konflik agraria yang terjadi, seperti di Rempang, Wadas, dan Papua Selatan menunjukkan bagaimana negara sering kali lebih membela perusahaan ketimbang rakyatnya sendiri. Petani dan masyarakat adat yang berjuang mempertahankan tanah mereka justru dikriminalisasi dan menghadapi kekerasan dari aparat.
Selain kasus di atas ada juga kasus yang serupa yang tercatat dalam jurnal Astuti 2011, dimana ada beberapa contoh kekerasan kasus sengketa tanah yaitu
- Pada tahun 2007 Sejumlah anggota TNI AU bentrok dengan warga di kampung Cibitung Desa Sukamulya Kecamatan rumpin Kabupaten Bogor Jawa barat, karena sengketa lahan seluas 1000 Hektar. Dua warga terluka dalam kerusuhan tersebut (TNI menawarkan dana 1,6 milyar kepada warga sebagai kompensasi pembangunan fasilitas latihan dan markas komando)
- Pada tahun 2008 Warga Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan Jawa Timur menolak Tawaran relokasi terkait sengketa lahan di kawasan pusat tempur TNI AL. (warga kalah diPengadilan Tinggi Surabaya dan perselisihan berlanjut dengan empat korban tewas. Pengadilan memvonis 13 marinir paling berat tiga tahun penjara).
Selama beberapa dekade terakhir, perjuangan agraria tidak lagi hanya berfokus pada isu pertanian semata. Kini, gerakan petani juga harus berhadapan dengan eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan tambang serta kebijakan konservasi yang justru berorientasi pada keuntungan kapitalis. Dalam hal ini, perusahaan yang merusak lingkungan sering kali berusaha mencitrakan diri sebagai pelindung alam demi mendapatkan keuntungan dari skema konservasi. Ini menjadi bentuk lain dari neoliberalisme, di mana perusahaan tidak hanya menguasai lahan, tetapi juga mengontrol narasi mengenai perlindungan lingkungan.
Sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada petani. Meskipun secara teori hukum bisa menjadi alat perjuangan, kenyataannya hukum sering kali berpihak kepada pemilik modal. Negara, melalui aparat keamanan dan pejabat lokal, lebih sering menjadi “pelindung” perusahaan daripada rakyat yang mereka wakili. Fakta bahwa semakin banyak petani dan aktivis agraria dikriminalisasi setiap tahun menunjukkan betapa sulitnya mendapatkan keadilan dalam konflik agraria di Indonesia.
Isu lain yang turut menjadi perhatian adalah penuaan petani dan sulitnya regenerasi di sektor pertanian. Data menunjukkan bahwa mayoritas petani saat ini berusia di atas 40 tahun, sementara hanya sedikit anak muda yang tertarik untuk meneruskan usaha tani keluarga. Salah satu alasan utamanya adalah sulitnya akses terhadap lahan. Banyak pemuda dari keluarga petani yang akhirnya memilih untuk bekerja di sektor lain, seperti buruh bangunan atau pekerja informal di kota. Akibatnya, pertanian di Indonesia berisiko mengalami krisis tenaga kerja dalam 10-15 tahun ke depan.
Sistem pertanian korporasi yang semakin menguasai lahan-lahan pertanian di Indonesia. Petani kecil tidak benar-benar mandiri, melainkan terjebak dalam sistem ketergantungan terhadap perusahaan. Misalnya, dalam sistem perkebunan plasma, petani “dipaksa” bekerja untuk perusahaan dengan skema kontrak yang tidak adil. Infrastruktur pertanian sering kali dibiarkan rusak, membuat petani kesulitan mengangkut hasil panennya. Bahkan, petani yang bekerja dalam sistem ini sering mengalami eksploitasi ekonomi, di mana perusahaan dan pejabat lokal membebankan berbagai biaya tambahan yang membuat mereka semakin terhimpit.
Sebagai solusi, FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) mengusulkan penguatan sistem family Farming atau pertanian keluarga. Model ini dinilai lebih berkelanjutan dan mampu menjamin ketahanan pangan karena petani memiliki kontrol langsung atas lahannya. Namun, pertanian keluarga membutuhkan dukungan kebijakan yang lebih adil, termasuk reforma agraria, perlindungan lahan petani dari perampasan, dan kebijakan redistribusi tanah bagi mereka yang kehilangan lahannya.
Ada tiga langkah utama untuk mendukung pertanian keluarga di Indonesia. Pertama, redistribusi tanah melalui reforma agraria agar petani kecil memiliki lahan yang cukup untuk bertani. kedua, perlindungan terhadap wilayah pertanian agar petani tidak kehilangan akses akibat ekspansi perusahaan besar. Ketiga, pemulihan hak bagi petani yang telah kehilangan tanahnya melalui kebijakan restitusi atau kompensasi yang adil.
Tantangan utama dalam penerapan solusi ini adalah paradigma pembangunan di Indonesia yang masih berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan investasi dan pasar global. Negara lebih banyak mendukung perusahaan besar melalui berbagai kebijakan dan insentif, sementara petani kecil sering kali terpinggirkan. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka masa depan pertanian keluarga di Indonesia akan semakin terancam, dan petani kecil akan semakin kehilangan hak serta kemandirian mereka.