Bedah Artikel : Potensi Konflik Agraria Yang Terus Berlanjut Di Indonesia
Friday, 11 April 2025 , Admin
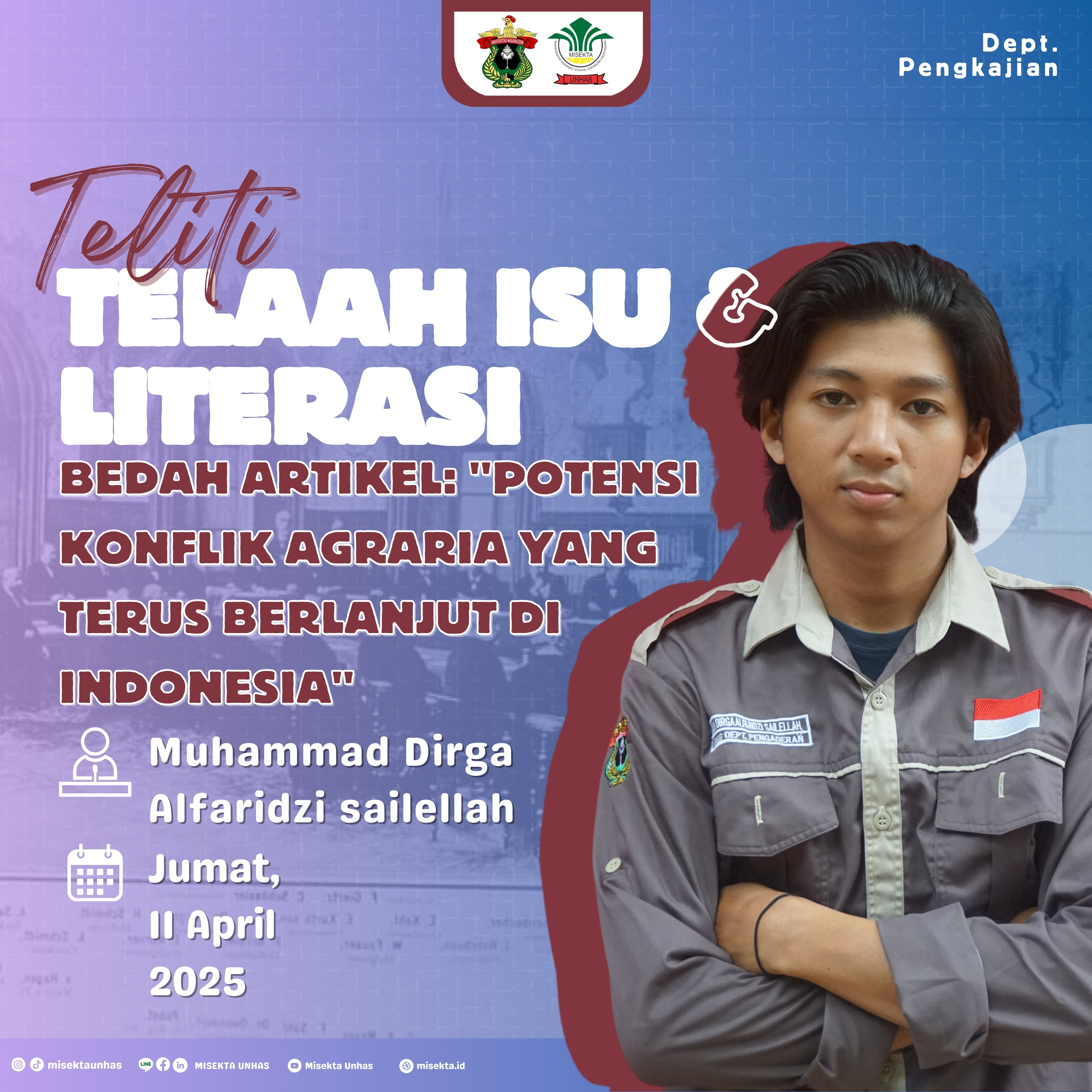
Konflik agraria yang terus terjadi di Indonesia merupakan manifestasi dari ketimpangan struktural dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam. Berdasarkan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang tahun 2024 terjadi 295 letusan konflik agraria, meningkat hampir 22% dibandingkan tahun sebelumnya. Mayoritas konflik tersebut terjadi di sektor perkebunan, terutama kelapa sawit, serta dalam proyek-proyek strategis nasional. Hal ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam mengatasi akar persoalan agraria meskipun berbagai kebijakan telah digulirkan.
Konflik agraria tidak hanya berimplikasi pada hilangnya tanah sebagai sumber penghidupan masyarakat, tetapi juga berdampak serius pada aspek sosial dan hak asasi manusia. Masyarakat, khususnya petani dan komunitas adat, kerap mengalami kekerasan, pengusiran paksa, hingga kriminalisasi akibat mempertahankan hak atas tanah yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Fenomena ini menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap rakyat kecil dalam menghadapi kepentingan modal dan pembangunan yang tidak inklusif.
Sebagai mahasiswa, penting untuk melihat persoalan agraria bukan hanya sebagai isu hukum atau administratif, melainkan sebagai persoalan keadilan sosial yang fundamental. Tanah memiliki makna yang lebih dari sekadar aset ekonomi; ia merupakan bagian dari identitas kultural dan eksistensi komunitas lokal. Ketika negara mengabaikan proses musyawarah dan persetujuan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait lahan, maka sesungguhnya negara telah lalai dalam menjalankan mandat konstitusionalnya.
Reforma agraria sejati harus melampaui sekadar program sertifikasi tanah. Pemerintah perlu melakukan redistribusi lahan secara adil, mengakui dan melindungi hak ulayat masyarakat adat, serta memberikan jaminan perlindungan terhadap komunitas yang rentan terhadap penggusuran. Sinkronisasi regulasi pertanahan dan keberpihakan nyata kepada rakyat kecil menjadi kunci untuk mengatasi ketimpangan struktural yang telah lama mengakar.
Konflik agraria juga mengungkap ketimpangan dalam struktur kekuasaan dan proses pengambilan keputusan. Perusahaan besar dan proyek-proyek strategis nasional sering kali memperoleh izin penguasaan lahan dengan mudah, sementara keberadaan masyarakat adat atau lokal yang telah lama mengelola wilayah tersebut diabaikan secara hukum. Lemahnya implementasi Undang-Undang Pokok Agraria serta tumpang tindih regulasi membuka celah bagi praktik perampasan lahan secara legal dan sistematis.
Dalam situasi tersebut, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial. Kampus harus menjadi ruang pengembangan kesadaran kritis dan keberpihakan terhadap isu-isu rakyat. Melalui kajian ilmiah, gerakan sosial, serta advokasi kebijakan, mahasiswa dapat menjadi jembatan antara masyarakat akar rumput dan pengambil kebijakan. Solidaritas antara akademisi, masyarakat sipil, dan komunitas lokal sangat penting untuk memperkuat perjuangan menuju keadilan agraria yang berkelanjutan.
Simpulan:
Konflik agraria di Indonesia mencerminkan persoalan struktural yang kompleks dan multidimensional, mencakup ketimpangan kekuasaan, lemahnya perlindungan hukum, serta minimnya keberpihakan negara terhadap masyarakat kecil. Upaya penyelesaian tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus berlandaskan pada prinsip keadilan sosial, pengakuan hak atas tanah, serta perlindungan hak asasi manusia. Peran aktif mahasiswa dan kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk mendorong terwujudnya reforma agraria yang sejati dan menciptakan tatanan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan.
Berita Terbaru
Artikel Terbaru
Bedah Artikel : Nenengisme dan Problemnya
Admin
24 April 2025




